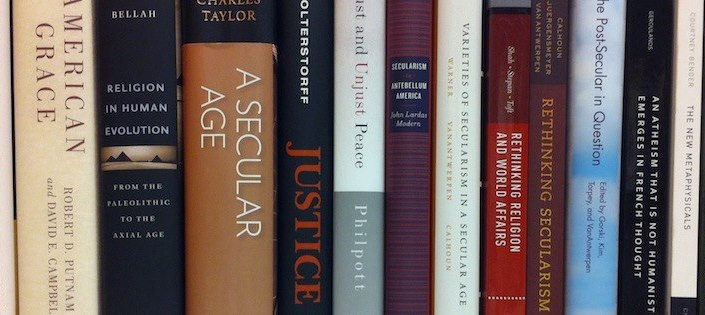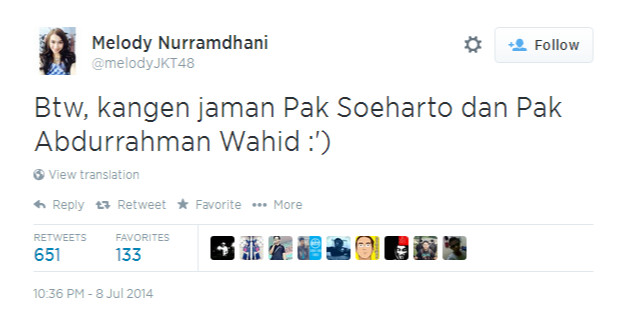Sewaktu kecil, saya adalah bocah yang sangat susah makan. Sebelum sendok makanan bisa masuk ke mulut saya, perhatian saya sering kali dialihkan, entah oleh tayangan TV atau pemandangan di jendela mobil. Ada seseorang yang lihai membantu ibu saya dalam urusan ini: Mbak Widati. Karena waktu kecil saya cadel, kami jadi memanggilnya Aid. Tiap kali saya dipegang Aid, makanan yang susah saya telan itu selalu berhasil mendarat masuk ke mulut–walau sering juga ujungnya sebagian terlepeh oleh saya.
Ibu saya adalah pekerja kantoran yang cukup sibuk. Semasa kecil hingga SD, waktu saya banyak dihabiskan bersama Aid dan nenek saya (saya biasa panggil Uti). Setiap hari Aid menunggu di depan gerbang sekolah, tempat antar-jemput anak-anak. Kadang bersama Uti. Ibu saya sementara itu disibukkan jika tidak dengan urusan kantor, maka dengan urusan perkooperasian di SD saat itu. Ibu saya waktu itu adalah pengurus koperasi.
Aid sudah mengurus saya hampir sejak saya dari lahir. Aid ibarat tante saya sendiri, jika tidak mau dibilang ibu kedua. Tiap ada urusan yang harus dikerjakan ibu saya tapi tidak bisa, Aid selalu menyikapinya dengan gesit. Kadang-kadang, Aid jadi penyeimbang bagi keputusan ibu saya yang kadang di luar akal. Pernah suatu hari, di tengah jalan sepulang dari liburan (sepertinya puncak), adik saya tiba-tiba ingin buang air besar. “Mau eek…” katanya merintih. Ibu saya, yang menyetir, langsung tancap gas pol-polan. Aid panik. “Nu jangan ngebut-ngebut!” Ybs punya ide lain: cari semak belukar, lalu biarkan adik buang air di sana.
Di rumah, Aid selalu duduk termangu (istilah Aid, ngglenuk) di depan TV. Biasanya pagi dan sore, di antara jeda pekerjaan rumah. Biasanya selalu ada cemilan seperti sambal dan ikan, serta segelas besar (gelas rootbeer A&W) es teh manis yang menemaninya menonton TV. Ibu saya sudah sering mengomeli Aid yang konsumsi gulanya luar biasa berlebihan, tapi namanya orang Jawa, sepertinya susah buat Aid buat menampik kebiasaan itu.
Di sore-sore seperti itu, saat saya sedang bermain Lego di dekatnya, kadang saya bertanya apa yang ditontonnya, saking seriusnya ybs terhenyak dalam tontonannya. Biasanya ybs tak berpanjang lebar menjawab saya. Aid yang agak gemuk dan berambut keriting pendek diikat itu hanya ngglenuk, asyik dengan tontonan dan makanannya.
Makanan bikinan Aid yang menjadi favorit saya adalah rawon. Aid sepertinya belajar dari juru masak paling andal di keluarga saya: Eyang Uti. Setiap kali Aid pulang kampung ke Klaten, kemudian kembali ke Jakarta, Aid selalu membawakan telor asin khas Klaten. Telor-telor asin itu kuning telornya berwarna merah, sedap sekali. Biasanya Aid akan memadukannya dengan rawon masakannya. Dulu saya selalu menanti masakan itu. Kadang-kadang bahkan saya gado, makan dengan lauknya saja, dan ujung-ujungnya saya habiskan. Aid sering mengomel kalau tahu saya mencuri jatah seperti itu. Katanya: jangan dihabiskan sendiri, pikirkan yang lain. Sepertinya omelan-omelan itu yang sekarang membuat saya jadi lebih sering menyisakan makanan yang dihidangkan di meja makan (walau cuma beberapa potong sih biasanya).
Aid senang sekali memberikan julukan pada saya dan adik saya. Saya biasa dipanggil “Gondel”. Entah apa artinya. Tapi mungkin merujuk pada bandelnya saya waktu kecil, dan juga isengnya saya. Saya pernah dengan ibu saya menakut-nakuti Aid dengan selimut, seperti pocong, di depan kamarnya. Jika sudah sebal, biasanya Aid akan bilang, dengan intonasi yang awalnya tinggi lalu makin merendah, ” Woooo, Gondel! Dasar…” Adik saya, di sisi lain, diberi julukan “Dimpu”. Saya juga tak tahu apa artinya, tapi bisa jadi karena terdengar lucu. Dim-nya sepertinya dari nama adik saya, Dimas.
Kadang-kadang saya cekcok dengan Aid. Biasanya kalau sudah urusan beberes rumah, yang sering kali terdapat miskomunikasi antara saya dengan ybs. Saya biasanya berucap kesal, “gimana sih Aid, gembel bener.” Saya waktu itu tidak mau menyebut “gemblung”, jadi saya mencari kata lain. Aid biasanya akan membalikkan, “gak apa-apa gembel, wong sugih!” Gembel adalah nama salah satu eyang saya yang cukup kaya raya.
Saat saya SMA, beranjak kuliah, Aid menikah. Setelah sekitar 17 tahun membesarkan saya dari lahir, akhirnya Aid meninggalkan rumah saya, hidup dengan kehidupannya sendiri. Suaminya hasil dari perjodohan yang dijodohkan orang tua saya. Ada masanya saya begitu kesal dengan keputusan itu–karena mendadak dan saya tidak dikabari–sehingga saya berteori konspirasi orang tua sengaja memisahkan saya dengan Aid.
Saya masih ingat waktu akhirnya Aid beranjak pergi dari rumah saya. Separuh berlinang air mata, Aid bilang, “kalo nanti udah jadi orang besar, jangan lupa sama Aid ya!” Aid waktu itu mencoba menutup air matanya dengan tawa. Memang, walau kadang judes dan menyebalkan, Aid adalah orang yang berusaha tampak ceria.
Suami Aid meninggal sekitar lima-enam tahun lalu. Tiap kali mengobrol singkat lewat telepon, kami selalu menyampaikan keinginan untuk bertemu satu sama lain. Aid kadang bercerita tentang sepinya di Klaten, dan kakinya yang sakit karena diabetes. Aid harus terus-menerus suntik insulin. Aid beberapa kali bilang bahwa ybs berencana untuk ke Jakarta ketika kondisinya sudah mendingan. Pada obrolan terakhir saya, Aid menyampaikan keinginannya untuk mampir ke Jakarta saat lebaran.
Seminggu terakhir saya entah kenapa teringat terus dengan Aid. Saya melihat udang yang dijual oleh kenalan saya, dan teringat makanan yang menemani tontonan Aid di TV pada sore hari. Saya ingin menelpon Aid, tapi rutinitas banal saya kerap menjadi excuse bagi saya untuk tidak melakukannya.
15 Januari 2021, ibu saya mencabut “uban pertama” di rambut saya. Saat itu saya tidak memikirkannya, tapi saya teringat waktu bertemu Aid yang beruban, dua atau tiga tahun lalu.
16 Januari 2021, saya mendapat kabar bahwa Aid meninggal dunia. Gagal ginjal.
Saya seharusnya menelpon beliau dari kemarin.
Saat ini saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa menulis tulisan pendek ini di blog.
Kalau Aid bisa entah bagaimana membaca tulisan ini, Aid harus tahu kalau Gondel kangen ya Aid. Gondel tadinya masih berharap Aid bisa melunasi janjinya untuk main ke sini. Sekarang aku cuma bisa berharap semoga Aid sudah tidak kesakitan lagi di sana.
Al-Fatihah.
Jakarta,
17 Januari 2021.


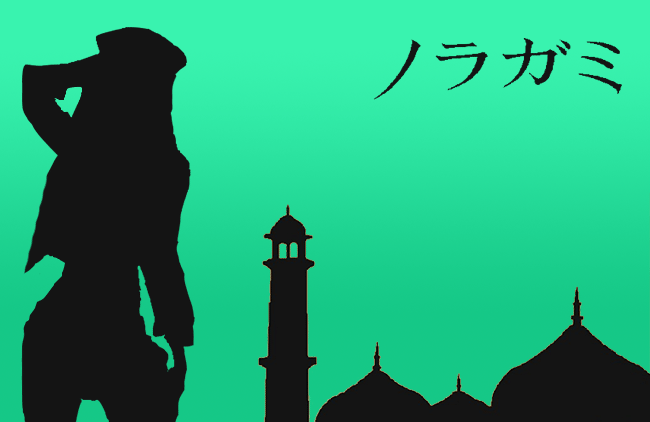
 Andai bisa menembus ruang dan waktu ke Indonesia hari ini, Kaisar Romawi Augustus (63 SM-14 M) yang semasa hidupnya bergelimang permata barangkali akan sangat terperanjat melihat batu akik yang dijual di emperan dan pasar, jauh dari kesan glamor dan kemuliaan. “Tidak menunjukkan nilai-nilai Romawi,” begitu mungkin gerutunya. Di masanya, perhiasan seindah itu hanya pantas berada di genggaman kerajaan atau di kuil-kuil megah yang dipersembahkan untuk dewa-dewi.
Andai bisa menembus ruang dan waktu ke Indonesia hari ini, Kaisar Romawi Augustus (63 SM-14 M) yang semasa hidupnya bergelimang permata barangkali akan sangat terperanjat melihat batu akik yang dijual di emperan dan pasar, jauh dari kesan glamor dan kemuliaan. “Tidak menunjukkan nilai-nilai Romawi,” begitu mungkin gerutunya. Di masanya, perhiasan seindah itu hanya pantas berada di genggaman kerajaan atau di kuil-kuil megah yang dipersembahkan untuk dewa-dewi.